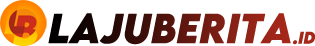Oleh : Dr. Noviardi Ferzi *
Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Aur Kenali, Kota Jambi, bukanlah perkara sederhana. Lokasinya yang hanya sekitar 700 meter dari intake PDAM—sumber air baku masyarakat—ibarat membangun bengkel mobil di samping sumur keluarga: sekalipun tidak selalu ada oli yang tercecer, risiko tercampurnya air tetap tinggi.
Logika sederhana ini kerap dilupakan. Klaim bahwa “investasi besar pasti aman” justru mirip keyakinan bahwa mobil mewah otomatis tidak bisa mengalami rem blong. Padahal, teknologi secanggih apapun tetap bergantung pada disiplin pelaksana dan kondisi lapangan.
Penelitian di Pelabuhan Koper, Slovenia, menunjukkan bahwa manuver kapal dapat meningkatkan kekeruhan air hingga 137 NTU, dengan kadar TSS mencapai 139 mg/L—angka yang tidak sesuai standar air baku (Petelin et al., 2023). Fakta ini mengingatkan kita bahwa air bersih tidak mengenal kompromi: sedikit saja tercemar, seluruh sistem pengolahan bisa terganggu.
Demikian pula anggapan bahwa intake PDAM aman karena berada di hulu tidak lebih dari penjelasan setengah matang. Sungai tidak seperti jalan raya lurus, melainkan seperti jaringan urat nadi dengan arus yang berputar, balik, dan menciptakan pusaran. Penelitian Brunner et al. (2022) membuktikan bahwa arus balik dan transportasi sedimen dapat membawa polutan ke arah yang tidak diduga, bahkan menuju titik yang seharusnya “aman”. Ini seperti menaruh racun di halaman belakang dengan keyakinan bahwa angin tidak akan pernah meniupnya ke ruang tamu.
Lebih jauh, pernyataan bahwa saat ini “belum ada pencemar” tidak menjawab persoalan inti. Sebuah dermaga yang belum beroperasi memang bersih, sebagaimana kompor baru yang belum pernah digunakan tidak meninggalkan asap. Namun, begitu aktivitas bongkar muat dimulai, ancaman tumpahan batubara, kebocoran bahan bakar, hingga sedimentasi akibat lalu lintas kapal adalah konsekuensi yang hampir pasti terjadi.
Pengalaman di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dermaga batubara berdampak langsung pada lonjakan kekeruhan yang mengganggu pasokan PDAM. Putra dan Arifin (2019) secara tegas menyebutkan: “aktivitas bongkar muat batubara di kawasan pelabuhan berdampak signifikan terhadap peningkatan kekeruhan air Sungai Barito, terutama pada musim hujan.”
PT SAS memang menyebutkan telah menyiapkan pemodelan hidrodinamika dan teknologi mitigasi. Namun, rencana di atas kertas seringkali hanya seperti janji pengendara untuk tidak ngebut: indah didengar, tetapi rawan dilanggar. Kasus reklamasi Teluk Jakarta memberi pelajaran jelas—meski dokumen Amdal dan mitigasi disusun rapi, kerusakan ekosistem tetap terjadi karena lemahnya implementasi (Hudalah & Firman, 2012).
Air baku PDAM adalah hajat hidup orang banyak. Sekali tercemar, biayanya bukan hanya soal uang, melainkan kesehatan masyarakat, menurunnya produktivitas, hingga meningkatnya konflik sosial. Perumpamaannya sederhana: jika sebuah rumah tangga kehilangan sumur air bersih, seluruh aktivitas lumpuh. Maka bagaimana dengan sebuah kota?
Karena itu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) harus menjadi pijakan utama. Pembangunan boleh saja mendorong ekonomi, tetapi harus diingat: nilai investasi dapat dihitung, sementara nilai air bersih tidak ternilai. Lebih bijak mencegah potensi pencemaran sejak awal ketimbang menyesal ketika kerusakan sudah tidak bisa dipulihkan. (*)
* Pemerhati Kebijakan Publik
Daftar Pustaka
Brunner, G., García, M. H., & De Cesare, G. (2022). Numerical and experimental study of flow patterns and sediment transport near intake structures. Environmental Fluid Mechanics, 22(5), 965–982. https://doi.org/10.1007/s10652-021-09839-7
Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. Cities, 29(1), 40–48. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.002
Petelin, S., Kovač, N., & Horvat, M. (2023). Sediment resuspension during vessel manoeuvres in port areas: A field study in Port of Koper. Marine Pollution Bulletin, 192, 115018. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115018
Putra, R. A., & Arifin, Z. (2019). Dampak kegiatan pelabuhan batubara terhadap kualitas air Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(1), 45–56. https://doi.org/10.14710/jil.17.1.45-56
Yuliani, E., & Suprapto, R. (2020). Pencemaran air permukaan akibat aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Indonesian Journal of Environmental Management, 7(2), 101–113. https://doi.org/10.22146/ijem.2020.7.2.101